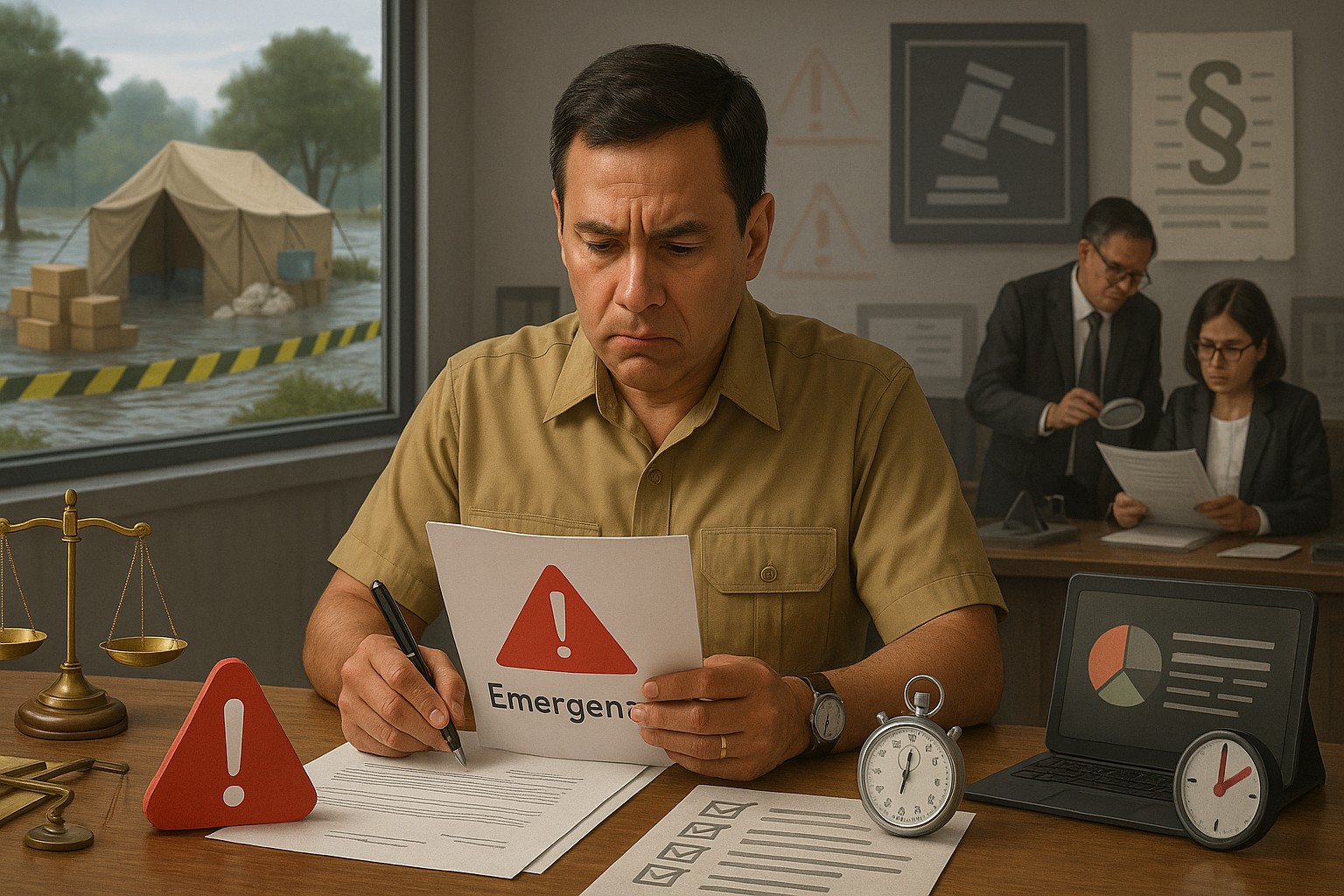Pengadaan barang dan jasa dalam situasi darurat sering kali menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik dan menanggapi bencana, wabah penyakit, atau situasi kritis lainnya dengan cepat. Namun, kecepatan yang menjadi tuntutan utama ini harus dilembangkan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Artikel ini memberikan uraian mendalam mengenai risiko hukum yang melekat pada pengadaan darurat serta strategi mitigasi yang perlu diterapkan agar proses pengadaan tetap sah, transparan, dan akuntabel.
1. Pengertian dan Ciri Pengadaan Darurat
Pengadaan darurat adalah suatu mekanisme dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dirancang untuk merespon kebutuhan secara cepat dalam situasi luar biasa, di mana metode pengadaan normal seperti tender umum, seleksi terbuka, atau lelang tidak mungkin dilakukan tanpa membahayakan keselamatan, keamanan, atau kelangsungan pelayanan publik. Dalam praktiknya, pengadaan darurat sering digunakan dalam situasi seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus), kebakaran besar, kerusuhan sosial, wabah penyakit menular (seperti pandemi COVID-19), kegagalan sistem vital (listrik, air bersih, layanan rumah sakit), hingga keadaan darurat non-alam yang ditetapkan oleh otoritas resmi.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan darurat merupakan salah satu metode khusus yang diperbolehkan tanpa melalui proses tender atau seleksi yang lazim. Namun, penggunaannya hanya dibenarkan jika memenuhi tiga syarat utama:
- Pertama, adanya kondisi mendesak yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan jiwa manusia, kelangsungan layanan publik, atau kerusakan lingkungan secara serius.
- Kedua, barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat ditunda hingga proses tender selesai.
- Ketiga, pengadaan tersebut harus segera dilaksanakan untuk mencegah atau meminimalkan dampak yang lebih besar.
Beberapa ciri khas pengadaan darurat yang membedakannya dari pengadaan reguler antara lain:
- Penyederhanaan proses administrasi: dokumen tender tidak wajib disusun lengkap, cukup dengan uraian kebutuhan, justifikasi keadaan darurat, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang wajar.
- Penunjukan langsung penyedia: pemilihan penyedia dilakukan secara langsung tanpa kompetisi terbuka. Hal ini tentu memangkas waktu, tetapi juga meningkatkan risiko konflik kepentingan atau pemilihan mitra yang tidak kapabel.
- Waktu pelaksanaan yang singkat: kegiatan pengadaan dapat dimulai secepat mungkin, bahkan sebelum dokumen lengkap disusun, selama dapat dibuktikan urgensinya.
- Fokus pada output, bukan prosedur: dalam pengadaan darurat, orientasi utama adalah hasil (barang/jasa tersedia tepat waktu), bukan kelengkapan dokumen di awal proses.
Namun, fleksibilitas ini bukan tanpa risiko. Karena ruang kontrol dan verifikasi dipersempit akibat keterbatasan waktu, potensi penyalahgunaan seperti markup harga, pengadaan fiktif, atau penunjukan penyedia yang tidak memenuhi standar teknis menjadi semakin besar. Oleh karena itu, meskipun disebut “darurat”, setiap proses tetap wajib memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money, serta menyusun dokumentasi retrospektif (setelah pelaksanaan) sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Landasan Hukum dan Batasan Pengadaan Darurat
Untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pengadaan darurat tetap dalam koridor hukum, terdapat sejumlah kerangka regulasi yang menjadi acuan utama. Landasan hukum ini penting bukan hanya sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum bagi pejabat pengadaan agar tidak terjebak dalam pelanggaran prosedural yang berujung pada temuan audit atau sanksi pidana.
Regulasi yang menjadi dasar hukum pengadaan darurat di antaranya:
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres PBJ): mengatur secara spesifik tentang mekanisme pengadaan darurat sebagai salah satu metode pengadaan langsung. Pasal-pasal dalam Perpres ini menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, tahapan formal dapat disederhanakan asalkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas tetap terpenuhi.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): memuat pedoman teknis, formulir standar, dan protokol khusus dalam pelaksanaan pengadaan darurat, termasuk dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan pasca-pelaksanaan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK): mengatur tata cara pengelolaan anggaran belanja negara termasuk belanja tidak terduga, pos darurat, dan tata cara pencairan dana dalam kondisi bencana atau krisis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018: khususnya untuk pengadaan darurat di lingkup desa dan pemerintah daerah.
Selain memahami regulasi, penting juga memahami batasan pengadaan darurat, baik dari sisi nilai anggaran, jenis barang/jasa, maupun dokumen pengesahan. Beberapa batasan yang harus diperhatikan meliputi:
- Nilai maksimal pengadaan: Pengadaan darurat biasanya dibatasi pada jumlah tertentu, misalnya maksimal Rp200 juta untuk swakelola desa atau maksimal Rp2,5 miliar untuk satu paket pengadaan langsung di instansi pusat/daerah. Jika kebutuhan melampaui batas, harus dilakukan pengajuan anggaran tambahan atau menggunakan metode pengadaan reguler.
- Jenis barang/jasa yang diperbolehkan: Hanya pengadaan yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana atau layanan vital yang dapat menggunakan mekanisme darurat. Pengadaan perlengkapan rutin, kendaraan dinas, atau belanja operasional biasa tidak termasuk.
- Justifikasi tertulis: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala OPD wajib menyusun dokumen justifikasi keadaan darurat, biasanya dalam bentuk Surat Pernyataan Keadaan Darurat atau Surat Keputusan Kepala Daerah, disertai kronologi, daftar kebutuhan, dan estimasi waktu penanganan.
- SPK Internal dan Surat Penunjukan Penyedia: Harus diterbitkan sebelum pencairan dana dilakukan. Dokumen ini akan menjadi dasar legalitas pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan pertanggungjawaban di kemudian hari.
- Pelaporan dan evaluasi: Setelah pelaksanaan selesai, wajib dilakukan evaluasi menyeluruh dan penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan darurat, termasuk dokumen pendukung seperti faktur, berita acara serah terima, dan dokumentasi lapangan.
Pelanggaran terhadap batasan tersebut, misalnya dengan memecah-mecah paket agar bisa ditunjuk langsung, atau menetapkan keadaan darurat tanpa dasar hukum yang jelas, dapat dinyatakan sebagai penyimpangan dalam audit BPK maupun pemeriksaan Inspektorat. Bahkan, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, proses ini bisa ditindaklanjuti ke ranah pidana dengan dasar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Karena itulah, pengadaan darurat meskipun terkesan lebih fleksibel dan cepat, tetap harus dijalankan dengan disiplin prosedur yang ketat, didukung dokumentasi yang valid, dan pengawasan internal yang memadai. Prinsip dasarnya adalah: percepat proses tanpa mengorbankan integritas.
3. Risiko Hukum Utama dalam Pengadaan Darurat
Pelaksanaan pengadaan darurat memang dirancang untuk fleksibilitas dan kecepatan. Namun, di balik keistimewaan itu, terdapat berbagai potensi risiko hukum yang bisa muncul apabila prosesnya tidak dikawal dengan kehati-hatian dan ketelitian. Risiko ini bisa bersifat administratif, perdata, hingga pidana, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kelalaiannya.
3.1. Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Melawan Hukum
Karena sistem pengadaan darurat memberikan keleluasaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala Dinas untuk langsung menunjuk penyedia, maka ruang subjektivitas dalam pengambilan keputusan menjadi lebih besar dibandingkan pengadaan reguler. Jika tidak ada pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, kewenangan ini rawan disalahgunakan untuk memilih mitra kerja yang memiliki hubungan dekat, atau bahkan untuk memperoleh gratifikasi pribadi dari penyedia. Praktik seperti ini secara langsung masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang, yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pejabat yang terbukti menunjuk penyedia secara tidak sah, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat dipidana meskipun barang sudah tersedia.
Selain itu, penggunaan dalih keadaan darurat untuk menutupi motif keuntungan pribadi juga masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, yang membuka ruang gugatan secara perdata oleh masyarakat, LSM, atau pihak penyedia lain yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legal dalam pengadaan darurat tidak bisa dianggap ringan hanya karena situasinya luar biasa.
3.2. Dokumen Tidak Lengkap dan Kecacatan Administratif
Pengadaan darurat memang mengizinkan adanya penyederhanaan dokumen, namun bukan berarti penghapusan total. Setiap keputusan tetap harus didasari oleh dokumen seperti kajian kebutuhan, justifikasi kondisi darurat, perbandingan harga, dan surat penunjukan penyedia. Jika dokumen-dokumen ini tidak tersedia atau hanya disusun secara asal-asalan, maka akan menimbulkan celah bagi auditor (baik SPI maupun BPK) untuk menyatakan prosesnya cacat administratif.
Cacat administratif dalam pengadaan tidak hanya berujung pada penghentian pembayaran atau pengembalian anggaran, tetapi juga dapat mencoreng reputasi pejabat yang bersangkutan dan memicu pemeriksaan lanjutan. Dalam kasus tertentu, dokumen yang tidak lengkap juga bisa dianggap sebagai indikasi awal dari praktik mark-up, pengadaan fiktif, atau persekongkolan.
3.3. Konflik Kepentingan dan Kurangnya Transparansi
Dalam kondisi krisis, tekanan waktu dan kebutuhan cepat sering menyebabkan langkah-langkah transparansi diabaikan. Proses pengadaan yang tertutup, tanpa publikasi nama penyedia, nilai kontrak, atau jadwal pelaksanaan, menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Ketika informasi publik tidak disediakan, masyarakat dan auditor sulit melakukan kontrol sosial, yang berujung pada dugaan konflik kepentingan.
Jika terbukti bahwa pejabat pengadaan memiliki hubungan langsung dengan penyedia (baik hubungan keluarga, bisnis, maupun afiliasi politik), maka pengadaan bisa dibatalkan dan pejabat yang bersangkutan dikenai sanksi etika maupun hukum. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya tuntutan publik, tetapi alat perlindungan hukum agar proses darurat tidak menimbulkan kecurigaan.
3.4. Ketidaksesuaian Spesifikasi dan Kualitas Barang/Jasa
Kecepatan dalam proses darurat sering kali menyebabkan spesifikasi teknis disusun secara terburu-buru atau bahkan hanya berdasarkan deskripsi verbal. Hal ini sangat berisiko terutama jika barang yang dibeli bersifat teknis tinggi atau menyangkut keselamatan publik (seperti alat kesehatan, bangunan darurat, atau air bersih).
Jika barang yang diterima ternyata tidak sesuai, cacat, atau gagal fungsi, maka proses klaim jaminan (guarantee claim) bisa menjadi sulit karena kontrak tidak secara rinci mencantumkan standar kualitas dan tanggung jawab penyedia. Sengketa dapat muncul antara penyedia dan pengguna barang, dan bila tidak diselesaikan baik-baik, bisa bermuara pada gugatan hukum atau pelaporan ke aparat penegak hukum.
3.5. Penggunaan Anggaran Tidak Sesuai Peruntukan
Risiko besar lain dalam pengadaan darurat adalah penggunaan anggaran di luar konteks kedaruratan. Misalnya, menggunakan dana tanggap bencana untuk membiayai pengadaan mebel kantor, seragam pegawai, atau kegiatan rapat. Meskipun barang/jasa tersebut ada dalam daftar kebutuhan instansi, jika tidak relevan dengan darurat yang ditetapkan, maka dianggap menyalahi peruntukan anggaran.
Penggunaan anggaran tidak sesuai dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan UU Keuangan Negara, mulai dari pemotongan dana transfer daerah, tuntutan ganti rugi, hingga sanksi pidana apabila ada unsur memperkaya diri atau pihak lain. Bahkan jika tidak ada niat jahat, pejabat tetap bisa diminta pertanggungjawaban administratif dan pengembalian dana, karena dianggap lalai.
4. Strategi Mitigasi Risiko Hukum
Untuk menghindari risiko hukum yang berpotensi serius, instansi pemerintah harus menerapkan langkah-langkah mitigasi hukum secara sistematis bahkan dalam situasi darurat. Mitigasi bukan hanya untuk membela diri saat terjadi audit, tapi juga untuk menjaga integritas tata kelola pengadaan publik secara keseluruhan.
4.1. Penyusunan Dokumen Keputusan Darurat yang Komprehensif
Langkah pertama adalah memastikan bahwa keputusan untuk melakukan pengadaan darurat terdokumentasi secara formal dan lengkap. Pejabat pengadaan harus membuat dokumen seperti Nota Dinas, Surat Penetapan Darurat, dan Justifikasi Teknis, yang menjelaskan:
- Kronologi kejadian darurat
- Alasan tidak mungkin menggunakan pengadaan reguler
- Kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi
- Alternatif penyedia yang dipertimbangkan
- Estimasi biaya berdasarkan harga pasar
Dokumen ini menjadi benteng pertama pembelaan hukum jika suatu saat proses pengadaan dipertanyakan atau diaudit oleh BPK, KPK, atau aparat penegak hukum lainnya.
4.2. Pelibatan Pengawasan Internal dan Eksternal
Pengawasan adalah jantung dari tata kelola pengadaan. Dalam kondisi darurat, pelibatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Inspektorat Daerah menjadi penting untuk melakukan verifikasi dokumen, memastikan penyedia dipilih secara wajar, dan menilai kewajaran harga. Bahkan, beberapa instansi sudah menerapkan pre-audit atau rapid audit sebelum pencairan anggaran untuk memastikan prosedur minimum telah dipenuhi.
Dengan melibatkan pengawasan sejak awal, risiko penyimpangan bisa ditekan, dan tanggung jawab tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja.
4.3. Transparansi Proaktif
Keterbukaan informasi adalah langkah pencegahan yang sangat efektif terhadap dugaan penyalahgunaan. Bahkan dalam kondisi krisis, instansi sebaiknya tetap mempublikasikan informasi pengadaan melalui:
- Website resmi pemerintah
- Portal LPSE lokal atau nasional
- Papan pengumuman kantor desa atau kelurahan
Informasi yang dipublikasikan sebaiknya meliputi nama penyedia, nilai kontrak, ringkasan pekerjaan, dan jangka waktu pelaksanaan. Transparansi ini menjadi bukti bahwa proses dilakukan secara terbuka dan dapat dikontrol publik.
4.4. Checklist dan Prosedur Internal Darurat
Setiap instansi perlu menyusun checklist minimum untuk pengadaan darurat yang wajib dipatuhi tanpa pengecualian. Checklist ini mencakup dokumen seperti:
- RAB darurat yang realistis
- Berita acara survei harga
- Surat bebas konflik kepentingan
- Surat penunjukan penyedia
- SPK dan kontrak kerja
Checklist ini bisa disusun dalam format Excel atau Google Sheet dan dipantau langsung oleh pejabat pengendali teknis. Dengan alat ini, tidak ada tahapan yang terlewat meski dalam tekanan waktu.
4.5. Penegasan Kontrak dengan Klausul Mutu dan Jaminan
Walaupun prosesnya cepat, kontrak pengadaan darurat tetap wajib mengatur standar mutu barang/jasa, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme ganti rugi jika penyedia gagal memenuhi kewajiban. Tambahkan klausul tentang:
- Jaminan teknis atau garansi minimal 3-6 bulan
- Penalti atau denda keterlambatan
- Kewajiban penggantian barang cacat tanpa biaya tambahan
Klausul ini memastikan bahwa meskipun kondisi darurat, penyedia tetap bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Ini adalah bentuk perlindungan hukum jangka panjang bagi pengguna anggaran.
5. Studi Kasus: Pengadaan Alkes pada Masa Pandemi
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 menjadi contoh nyata bagaimana situasi darurat menuntut fleksibilitas tinggi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah pengadaan alat kesehatan (alkes), termasuk masker medis, alat pelindung diri (APD), ventilator, dan reagen laboratorium.
Di salah satu kabupaten di Indonesia, pemerintah daerah memutuskan untuk menggunakan skema pengadaan darurat dalam memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan dan warga. Penunjukan penyedia dilakukan tanpa melalui proses tender, dengan alasan bahwa waktu sangat mendesak dan pasokan terbatas secara nasional. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kontrak ditandatangani dan proses pengiriman dimulai. Namun, audit yang dilakukan beberapa bulan kemudian oleh Inspektorat Daerah mengungkap sejumlah persoalan serius:
- Tidak adanya dokumen pembanding harga dari setidaknya dua penyedia lain yang relevan, padahal harga masker N95 yang dibeli ternyata mencapai Rp150.000 per unit, padahal harga pasaran saat itu Rp50.000-60.000.
- Spesifikasi teknis yang tidak konsisten, di mana jenis masker yang diterima bukan tipe N95 asli melainkan masker KN95 non-sertifikasi.
- Distribusi yang tertunda selama lebih dari dua minggu, karena barang dikirim sebagian dan tanpa sistem pencatatan logistik yang jelas.
- Tidak adanya bukti pembayaran pajak dan retensi dalam dokumen tagihan yang diajukan penyedia, padahal nominal kontrak cukup besar (miliaran rupiah).
Akibatnya, Inspektorat menunda pencairan pembayaran termin kedua, dan meminta pejabat pengadaan serta penyedia untuk menjelaskan detail transaksi. Setelah proses klarifikasi, ditemukan adanya potensi mark-up harga sebesar 200% dan ketidaksesuaian spesifikasi. Pejabat pengadaan diminta untuk mengembalikan kelebihan anggaran melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan sebagian dana dikembalikan ke kas daerah.
Dari kasus ini dapat ditarik beberapa pelajaran penting:
- Pengadaan darurat bukan pembenaran untuk meniadakan dokumentasi. Justru karena pengawasan dilakukan pasca-kegiatan, dokumentasi seperti survei harga, spesifikasi teknis, dan alur distribusi menjadi kunci utama untuk membuktikan bahwa pengadaan dilakukan secara wajar dan sah.
- Penunjukan langsung tetap harus dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan harga, bukan sekadar kedekatan atau kemudahan akses ke penyedia.
- Audit internal harus dilakukan secara paralel (concurrent audit) selama proses pengadaan berlangsung, bukan hanya setelah semua anggaran habis.
- Kapasitas SDM pengadaan harus ditingkatkan, terutama dalam memahami dasar hukum, dokumen wajib, dan risiko hukum dari tindakan yang diambil, meskipun dalam kondisi darurat.
Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa ketergesaan dan tekanan keadaan seringkali menjadi celah masuknya pelanggaran, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi tetap tidak boleh dilupakan, sekalipun dalam konteks krisis nasional sekalipun.
6. Kesimpulan
Pengadaan darurat merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya saat menghadapi bencana, wabah penyakit, atau kondisi lain yang mengancam keselamatan publik dan kelangsungan layanan dasar. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur bahwa mekanisme ini dapat digunakan sebagai pengecualian dari metode reguler. Namun, keistimewaan ini juga membawa konsekuensi hukum dan akuntabilitas yang tinggi.
Risiko hukum dalam pengadaan darurat sangat beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, cacat administratif, konflik kepentingan, hingga penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan. Semua risiko ini tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengarah pada sanksi pidana, terutama bila terbukti terjadi kolusi, mark-up, atau pengadaan fiktif.
Oleh karena itu, penting bagi semua pelaku pengadaan, mulai dari kepala daerah, PPK, pejabat pengadaan, hingga bendahara dan auditor, untuk mengadopsi strategi mitigasi hukum yang tepat. Strategi tersebut meliputi:
- Penyusunan dokumen yang komprehensif, termasuk analisis kebutuhan, justifikasi keadaan darurat, dan perbandingan harga pasar.
- Pelibatan pengawasan internal (SPI) dan eksternal (BPK, Inspektorat) sejak awal proses pengadaan, bukan hanya saat audit akhir.
- Transparansi proaktif, seperti publikasi data penyedia dan rincian kontrak di media resmi pemerintah, untuk membangun kepercayaan publik.
- Kontrak yang rinci dan adil, dilengkapi dengan klausul mutu, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
- Checklist internal untuk memastikan bahwa prosedur minimum tetap dijalankan secara konsisten, meskipun dalam situasi darurat.
- Evaluasi berkala dan pembelajaran dari kasus-kasus terdahulu, agar kesalahan yang sama tidak terulang.
Pada akhirnya, pengadaan darurat harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Kecepatan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan wajib memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien, efektif, dan tidak melanggar prinsip-prinsip good governance.
Dengan pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab, pengadaan darurat tidak hanya akan menyelamatkan nyawa dan aset publik dalam kondisi krisis, tetapi juga dapat menjadi bukti bahwa negara hadir dengan mekanisme yang cepat namun tetap taat aturan. Prinsip inilah yang menjadi pondasi bagi penyelenggaraan pengadaan publik yang terpercaya dan berkelanjutan, baik dalam kondisi normal maupun darurat.