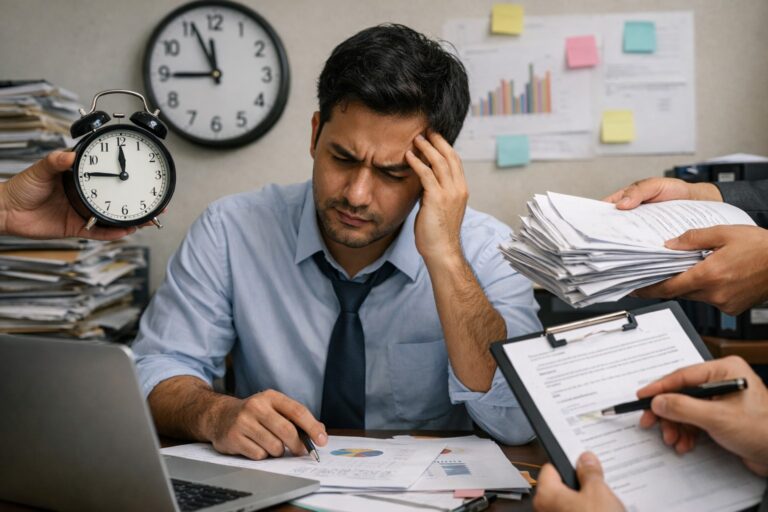Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia menghadapi beragam tantangan, namun tantangan tersebut menjadi jauh lebih kompleks saat dilakukan di Daerah 3T-yaitu wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Daerah 3T mencakup provinsi atau kabupaten yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan, batas negara, atau berada di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas; sering kali juga merupakan wilayah yang belum mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang memadai. Kondisi inilah yang menjadikan proses pengadaan barang/jasa untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, maupun bantuan sosial menjadi sangat menantang. Artikel ini akan membahas secara mendalam berbagai kendala yang dihadapi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan PBJ di daerah 3T, mulai dari kerangka regulasi, kendala logistik dan geografis, kapasitas SDM, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, hingga strategi mitigasi yang perlu diterapkan.
1. Karakteristik Daerah 3T dan Implikasinya bagi Proses Pengadaan
Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sangat berbeda dari daerah-daerah maju seperti kota-kota besar di Pulau Jawa. Ciri khas utama dari daerah 3T adalah keterisolasian baik secara fisik maupun sistemik dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Isolasi ini bukan hanya sekadar jarak, melainkan juga karena keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, fasilitas komunikasi, hingga jaringan listrik. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, hal ini berdampak langsung pada semua tahapan siklus pengadaan, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan.
- Jarak geografis dan medan berat menciptakan hambatan yang signifikan dalam distribusi logistik. Sebuah kegiatan pengadaan yang di kota besar mungkin hanya memakan waktu seminggu, di daerah 3T bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Contohnya, pengadaan alat kesehatan di Pegunungan Bintang, Papua, tidak hanya harus menunggu persetujuan administrasi tetapi juga harus menghadapi tantangan mengangkut barang melalui jalur udara atau jalan darat berlumpur yang kadang tidak dapat dilalui sama sekali saat musim hujan. Biaya pengiriman menjadi sangat mahal karena terbatasnya moda transportasi dan tidak adanya skala ekonomi.
- Keterbatasan teknologi informasi adalah kendala besar yang berdampak langsung pada implementasi sistem pengadaan elektronik (e-procurement). SPSE dan e‑catalogue yang menjadi tulang punggung transparansi dan efisiensi pengadaan tidak dapat dijalankan optimal bila akses internet tidak tersedia atau tidak stabil. Di banyak wilayah 3T, bahkan sinyal telepon seluler masih lemah atau tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada proses manual, yang selain tidak efisien juga meningkatkan risiko kesalahan input, keterlambatan administratif, dan celah manipulasi data.
- Kapasitas sumber daya manusia di unit kerja pengadaan masih sangat terbatas. Banyak pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, atau staf administrasi belum memiliki sertifikasi PBJ atau pengalaman cukup dalam mengelola dokumen tender yang kompleks. Ketika kebijakan pengadaan tidak disosialisasikan secara menyeluruh, atau perubahan regulasi terbaru tidak cepat diketahui oleh pelaksana lapangan, maka risiko kesalahan prosedural meningkat. Bahkan, dalam banyak kasus, staf PBJ juga merangkap pekerjaan di bidang lain, karena jumlah pegawai yang minim, sehingga fokus terhadap proses pengadaan menjadi terbagi.
- Struktur ekonomi lokal yang belum berkembang menyebabkan kurangnya pelaku usaha yang mampu mengikuti proses tender. Penyedia barang/jasa lokal sering tidak memiliki perizinan formal, sistem akuntansi yang rapi, atau kemampuan mencetak dokumen penawaran sesuai format yang diharuskan oleh sistem pengadaan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, partisipasi penyedia lokal menjadi sangat terbatas, dan akibatnya paket pengadaan diserahkan kepada penyedia dari luar daerah yang justru meningkatkan biaya transportasi dan mengurangi efek multiplier ekonomi lokal. Selain itu, hal ini menyebabkan kegiatan pengadaan gagal berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah.
Dengan mempertimbangkan semua karakteristik ini, maka sangat jelas bahwa pendekatan pengadaan di daerah 3T tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah maju. Setiap aspek perlu adaptasi khusus yang mempertimbangkan keterbatasan struktural, sosial, dan geografis secara menyeluruh.
2. Kerangka Regulasi dan Adaptasi di Daerah 3T
Regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku secara nasional memang memberikan kerangka kerja yang seragam dan prinsip dasar yang adil, seperti efisien, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan teknis regulasi tersebut dalam konteks daerah 3T sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk penyesuaian regulasi atau kebijakan operasional yang kontekstual menjadi penting agar prinsip-prinsip pengadaan tetap terlaksana dengan realistis dan berdampak nyata.
Salah satu bentuk adaptasi regulasi adalah penerapan metode pengadaan langsung untuk paket-paket bernilai rendah. Di wilayah 3T, hal ini menjadi opsi realistis karena menghindari proses tender terbuka yang kompleks dan tidak selalu menarik penyedia dari luar daerah karena faktor lokasi yang jauh. Namun, perlu dipastikan bahwa metode pengadaan langsung tetap dijalankan secara tertib administrasi, memiliki dokumentasi yang lengkap, dan diawasi secara berkala.
Selain itu, skema swakelola, terutama swakelola tipe III (melibatkan kelompok masyarakat), dapat menjadi pendekatan strategis. Kegiatan seperti pembangunan jalan lingkungan, pengadaan bahan makanan lokal, atau perbaikan sarana air bersih dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dengan pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pengadaan tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
Namun, semua bentuk adaptasi tersebut harus dibingkai dalam sistem pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi keharusan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), inspektorat daerah, dinas teknis terkait, dan kepala desa atau camat harus membangun mekanisme kerja sama yang mempercepat proses tanpa mengorbankan integritas. Dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah bagaimana menyelaraskan tanggung jawab ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah.
Penting juga untuk dicatat bahwa peran pemerintah pusat sangat krusial dalam memastikan bahwa daerah 3T tidak ditinggalkan dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Melalui LKPP, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, perlu disusun panduan teknis khusus pengadaan untuk daerah 3T yang bersifat fleksibel namun tetap menjamin akuntabilitas. Misalnya, memperbolehkan tenggat waktu yang lebih longgar, memfasilitasi koneksi internet satelit untuk kegiatan pengadaan, atau menyediakan konsultan pengadaan yang secara khusus bertugas mendampingi kabupaten/kota 3T.
Tanpa regulasi adaptif, daerah 3T akan terus mengalami ketertinggalan dalam belanja pemerintah yang semestinya menjadi pengungkit pembangunan. Oleh sebab itu, kebijakan khusus berbasis keadilan bukan hanya urusan teknis administratif, tetapi bagian dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
3. Kendala Logistik dan Infrastruktur Fisik
3.1. Akses Jalan dan Transportasi
Di banyak wilayah 3T, infrastruktur jalan seringkali dalam kondisi rusak berat, tidak beraspal, atau bahkan belum tersedia sama sekali. Akses menuju desa terpencil dapat mengharuskan tim logistik melintasi sungai tanpa jembatan, menyewa perahu, atau berjalan kaki berjam-jam. Hal ini membuat waktu tempuh menjadi sangat tidak terprediksi dan menghambat kelancaran pengiriman barang. Selain itu, cuaca buruk seperti hujan deras dan badai tropis dapat menutup akses transportasi selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan atau material proyek yang mendesak.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merancang sistem logistik yang fleksibel, misalnya dengan membangun gudang transit di lokasi strategis yang dapat diakses dari beberapa arah, atau menyewa moda transportasi alternatif seperti kendaraan off-road, kapal kecil, atau helikopter milik TNI dalam situasi darurat. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas jalan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan gantung atau dermaga lokal menjadi investasi penting untuk mempercepat pengadaan dan pelayanan publik di daerah 3T.
3.2. Infrastruktur Gudang dan Penyimpanan
Ketersediaan gudang logistik yang memadai menjadi prasyarat utama dalam mendukung kelancaran distribusi barang di daerah 3T. Sayangnya, banyak wilayah masih belum memiliki fasilitas penyimpanan yang layak. Barang bantuan sering ditumpuk di kantor desa, balai pertemuan, atau rumah warga karena tidak tersedia gudang yang memenuhi standar penyimpanan. Hal ini meningkatkan risiko kerusakan barang, kontaminasi pangan, atau pemborosan akibat tidak terdatanya barang secara sistematis.
Solusi yang dapat diterapkan adalah pembangunan mini warehouse modular dengan konstruksi ringan, cepat dibangun, dan tahan cuaca. Gudang ini harus dilengkapi rak penyimpanan, ventilasi memadai, sistem pencatatan stok berbasis aplikasi sederhana, serta prosedur standar penyerahan barang kepada penerima manfaat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan kementerian teknis atau donor internasional untuk mendanai pembangunan gudang tersebut sebagai bagian dari program penguatan logistik daerah.
3.3. Keterbatasan Fasilitas Pelabuhan dan Bandara
Di banyak pulau terluar, pelabuhan hanya mampu menampung kapal kecil atau kapal rakyat, sementara dermaga tidak memiliki fasilitas crane atau forklift untuk bongkar muat barang berat. Hal ini menyulitkan distribusi peralatan besar seperti tower telekomunikasi, genset, atau alat konstruksi jalan. Bandara perintis pun umumnya hanya melayani pesawat kecil dengan jadwal terbatas, sehingga tidak bisa diandalkan sebagai jalur distribusi utama.
Untuk mengatasi hambatan ini, perencanaan pengadaan harus memasukkan analisis rantai pasok secara detail, termasuk simulasi moda transportasi multimoda yang menggabungkan jalur laut, darat, dan sungai. Pemerintah juga dapat menjalin kerja sama logistik terpadu dengan instansi seperti TNI AL, Basarnas, atau pihak swasta yang memiliki moda transportasi laut. Selain itu, perlu disusun peta logistik 3T berbasis GIS yang diperbaharui secara berkala agar proses perencanaan dan pengadaan tidak terputus dari realitas di lapangan.
4. Disparitas Kapasitas SDM dan Transfer Pengetahuan
Di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pengadaan barang/jasa (PBJ) menghadapi tantangan fundamental berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan minimnya alur transfer pengetahuan antarlembaga. Masalah ini tidak hanya menghambat efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memperbesar risiko administratif dan korupsi karena kurangnya pemahaman teknis yang memadai. Beberapa isu utama dalam hal kapasitas SDM dan solusi yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut:
4.1. Kekurangan Personel Terlatih
Salah satu masalah paling mendasar adalah jumlah personel pengadaan yang sangat terbatas. Banyak unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) di kabupaten atau kota wilayah 3T hanya memiliki satu hingga dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersertifikat, tanpa dukungan struktur Pokja atau tim teknis lain yang memadai. Akibatnya, beban kerja yang semestinya ditangani oleh tim terdistribusi harus dipikul oleh individu atau tim kecil, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan administratif, keterlambatan proses, dan potensi temuan dari audit internal maupun eksternal.
Masalah ini diperparah oleh tingginya angka mutasi atau rotasi personel ASN di wilayah 3T, yang membuat knowledge loss sering terjadi. Untuk mengatasi kondisi ini, peran pemerintah pusat dan provinsi sangat penting, terutama dalam mengalokasikan sumber daya teknis tambahan. Bentuk bantuan yang direkomendasikan antara lain adalah penugasan tenaga ahli secara periodik ke wilayah 3T, seperti konsultan LPSE untuk membantu operasional e-procurement, mentor dari LKPP untuk penguatan sistem pengadaan lokal, serta tenaga pendamping dari BPKP untuk mendukung akuntabilitas dan pelaporan.
Langkah lebih progresif bahkan bisa diambil dengan mengadopsi sistem secondment (penugasan temporer) ASN pengadaan dari wilayah maju ke daerah 3T selama 3-6 bulan untuk mentransfer keahlian secara langsung dan membina kader lokal.
4.2. Pelatihan Jarak Jauh dan Hybrid
Akses terhadap pelatihan PBJ yang berkualitas masih sangat terbatas di wilayah 3T. Sebagian besar program pelatihan tatap muka yang diselenggarakan oleh LKPP, BPSDM provinsi, atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hanya tersedia di kota-kota besar. Akibatnya, ASN dan pelaksana teknis di wilayah 3T sering tertinggal dari sisi pemutakhiran pengetahuan maupun penguasaan perangkat digital terbaru.
Untuk menjawab tantangan ini, model pelatihan jarak jauh atau blended learning menjadi solusi yang semakin relevan. Dalam pendekatan ini, materi pelatihan disediakan dalam bentuk video interaktif atau dokumen PDF melalui sistem Learning Management System (LMS), disertai kuota internet atau paket data yang disubsidi. Pelatihan online ini kemudian dipadukan dengan lokakarya luring singkat yang diadakan di pusat kecamatan atau kabupaten agar terjadi interaksi langsung antara fasilitator dan peserta.
Selain itu, materi pelatihan perlu disederhanakan dengan bahasa yang lebih komunikatif atau bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa lokal agar dapat lebih mudah dipahami oleh peserta dari latar belakang non-teknis. Penggunaan infografis, contoh kasus lokal, dan kuis adaptif juga dapat membantu mempercepat pemahaman peserta.
4.3. Mentoring dan Kolaborasi Asinkron
Kemajuan teknologi komunikasi menawarkan peluang besar untuk menjembatani kesenjangan geografis dalam pengembangan kapasitas SDM. Dalam konteks PBJ di daerah 3T, mentoring asinkron melalui platform seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom, atau Microsoft Teams dapat difungsikan sebagai ruang diskusi antara UKPBJ pusat, fasilitator LKPP, dan personel daerah secara rutin.
Skema mentoring ini bisa berjalan dengan skedul mingguan atau bulanan, di mana peserta dapat mengirim pertanyaan, mengakses pedoman terbaru, hingga mengunggah draft dokumen pengadaan untuk direview oleh mentor. Semua materi penting seperti peraturan terbaru, SOP, checklist, dan template dokumen juga dapat dikumpulkan dalam folder cloud (misalnya Google Drive atau OneDrive) yang bisa diakses kapan pun.
Inisiatif ini bukan hanya efisien secara biaya, tetapi juga inklusif karena membuka akses kepada daerah yang sebelumnya tidak terjangkau pelatihan konvensional.
5. Tantangan Digitalisasi dan Akses E‑Procurement
Salah satu pilar reformasi pengadaan di Indonesia adalah digitalisasi melalui penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Namun, di wilayah 3T, transformasi digital ini menghadapi rintangan besar baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan teknis. Alih-alih mempercepat proses, digitalisasi malah bisa menjadi hambatan bila tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan.
5.1. Keterbatasan Konektivitas Internet
Banyak wilayah 3T yang belum memiliki akses internet yang stabil. Ketergantungan pada jaringan 4G, yang belum tersedia secara merata, membuat penggunaan SPSE menjadi tidak konsisten. Akibatnya, proses unggah dokumen, pengisian data, atau akses ke dashboard e-Procurement sering kali terputus atau gagal total, menyebabkan keterlambatan dalam seluruh siklus pengadaan.
Sebagai solusi sementara, pemerintah daerah dapat membuka loket digital di kecamatan-kecamatan yang memiliki sinyal relatif stabil. Loket ini bertugas membantu unggah dokumen ke SPSE, pencetakan berita acara, hingga konsultasi teknis. Selain itu, pemanfaatan jaringan satelit seperti Palapa Ring dapat dioptimalkan melalui kerja sama dengan Kominfo dan operator lokal, sehingga memperluas jangkauan konektivitas ke wilayah terpencil.
Langkah lain adalah mengembangkan aplikasi SPSE versi ringan yang dapat berjalan pada jaringan rendah (low bandwidth), serta penyediaan offline sync tool-yakni aplikasi yang dapat menyimpan data secara lokal dan melakukan sinkronisasi otomatis begitu perangkat kembali terhubung ke jaringan.
5.2. Keamanan Data dan Keaslian Dokumen
Minimnya akses internet di daerah 3T memaksa sebagian besar dokumen pengadaan dikirim secara manual. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan data dan validitas dokumen. Kasus pemalsuan tanda tangan, penyisipan dokumen ilegal, atau penggunaan dokumen versi lama kerap terjadi karena tidak adanya sistem kontrol digital yang kuat.
Untuk menjawab hal ini, pemerintah perlu mengintegrasikan mekanisme verifikasi digital ke dalam proses manual. Contohnya adalah penyisipan QR-code unik di setiap dokumen pengadaan yang mengarah ke tautan verifikasi online. Selain itu, penggunaan 2-Factor Authentication untuk akun SPSE sangat krusial, terutama untuk mencegah login dari perangkat yang tidak sah.
Lebih lanjut, cap stempel elektronik yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat digunakan untuk menjamin keaslian dokumen, sekaligus mempercepat proses legalisasi tanpa harus dilakukan secara tatap muka.
6. Pendanaan, Realokasi, dan Penyusutan Anggaran
Aspek pendanaan menjadi tantangan besar dalam pengadaan di daerah 3T, terutama karena keterbatasan fiskal, mekanisme transfer yang lambat, dan belum fleksibelnya sistem pengelolaan anggaran daerah. Dalam konteks ini, perlu adanya penyesuaian mekanisme anggaran yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan mendesak di lapangan.
6.1. Penyerapan Anggaran yang Lambat
Salah satu indikator rendahnya efektivitas pengadaan di wilayah 3T adalah tingkat penyerapan anggaran yang jauh di bawah standar nasional. Prosedur birokratis, keterlambatan dokumen, serta kendala teknis dalam proses verifikasi menyebabkan banyak anggaran tidak terpakai hingga akhir tahun, sehingga harus dikembalikan ke kas negara.
Dampaknya tidak hanya pada angka realisasi, tetapi juga pada menurunnya kualitas pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, solusi jangka panjang adalah memperkuat otonomi fiskal desa melalui peningkatan alokasi Dana Desa dan pembentukan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk wilayah 3T yang memiliki skema pelaporan yang lebih sederhana dan berbasis output, bukan hanya input.
Di sisi teknis, perlu dikembangkan sistem monitoring real-time yang memungkinkan pelacakan progres pengadaan dan serapan anggaran di level kecamatan atau desa, sehingga potensi keterlambatan bisa dideteksi sejak awal.
6.2. Realokasi Anggaran Tak Terduga
Bencana alam atau krisis darurat lainnya sering memaksa pemerintah daerah melakukan realokasi anggaran secara cepat. Namun, prosedur yang ada saat ini masih memerlukan tahapan panjang, seperti persetujuan TAPD, pembahasan ulang bersama DPRD, dan perubahan APBD yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Padahal, dalam konteks darurat, kecepatan adalah segalanya. Maka, perlu ada petunjuk teknis realokasi anggaran darurat khusus untuk wilayah 3T yang memungkinkan pengambilan keputusan maksimal dalam 3 hari kerja, melalui mekanisme pembahasan daring dan digitalisasi persetujuan.
Selain itu, Pemda bisa membentuk Dana Tanggap Darurat PBJ yang fleksibel penggunaannya, dengan sistem pengadaan langsung atau e-purchasing yang telah disiapkan sebelumnya dalam daftar kebutuhan bencana (stand-by list).
7. Strategi Mitigasi dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan berbagai tantangan kompleks yang dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa di wilayah 3T-yang mencakup aspek geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, hingga keterbatasan anggaran dan regulasi yang terlalu baku-maka diperlukan serangkaian strategi mitigasi dan rekomendasi kebijakan yang dirancang secara spesifik, adaptif, dan implementatif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, melainkan juga membangun fondasi jangka panjang untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, inklusif, dan akuntabel di daerah-daerah yang selama ini termarjinalkan dari akses pembangunan.
- Pertama, dibutuhkan kebijakan khusus berbasis regulasi daerah yang secara eksplisit memberi ruang fleksibilitas dalam proses PBJ di wilayah 3T. Pemerintah daerah dapat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur tentang penyederhanaan dokumen tender untuk paket-paket prioritas di sektor-sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ringan. Penyederhanaan ini tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran terhadap tata kelola yang lemah, melainkan sebagai bentuk reformasi administratif yang kontekstual, dengan tetap mengedepankan prinsip dasar pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
- Kedua, penting untuk mengalokasikan dana cadangan khusus untuk PBJ di 3T, baik melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa (DDD). Minimal 10% dari porsi anggaran tersebut idealnya ditujukan untuk mendanai pengadaan barang rutin dan layanan pendukung yang seringkali diabaikan karena tidak tergolong sebagai proyek besar, seperti kebutuhan ATK sekolah, alat pelindung kerja bagi tenaga kesehatan, bahan pelatihan keterampilan warga, hingga alat peraga pembelajaran. Strategi ini juga dapat mencakup insentif anggaran bagi desa yang mampu menyelenggarakan pengadaan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk mendorong mereka menggunakan metode swakelola berbasis masyarakat.
- Ketiga, koordinasi terpadu lintas sektor dan lintas dinas harus dibangun secara sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Pengadaan Daerah 3T (Satgas PBJ 3T) yang melibatkan berbagai aktor seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Komunikasi dan Informatika, serta akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki fokus pada pembangunan wilayah tertinggal. Koordinasi lintas sektor ini akan mempercepat proses pemetaan kebutuhan, validasi data, perencanaan pengadaan, dan pelaksanaan monitoring yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks lokal.
- Keempat, penguatan mekanisme pengadaan melalui metode swakelola menjadi kunci pemberdayaan komunitas lokal. Khususnya untuk kegiatan non-teknis atau dengan risiko rendah seperti pembangunan sarana non-struktural (posyandu, taman belajar), pelatihan warga, penyusunan modul literasi, serta pengadaan makanan tambahan untuk balita. Pemerintah dapat mendorong penggunaan Swakelola Tipe I (oleh instansi pemerintah) dan Swakelola Tipe III (oleh kelompok masyarakat), sehingga sumber daya lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses penyediaan barang dan jasa. Mekanisme ini terbukti mampu menekan biaya, mempercepat pelaksanaan, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap hasil kegiatan.
- Kelima, peningkatan infrastruktur digital harus dijadikan prioritas utama, karena ketersediaan akses internet menjadi prasyarat untuk berjalannya sistem e-Procurement dan e-Purchasing seperti SPSE dan e-Katalog. Pemerintah pusat perlu mempercepat implementasi proyek Palapa Ring, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, serta pemasangan jaringan fiber optic di kabupaten dan kecamatan 3T yang hingga kini masih mengalami blank spot. Selain itu, dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyediakan insentif berupa voucher kuota internet atau akses Wi-Fi gratis di kantor-kantor desa, terutama bagi aparatur desa yang sedang menjalankan proses pengadaan secara daring.
- Keenam, penting untuk menjamin keberlanjutan pendampingan teknis oleh tenaga ahli PBJ secara periodik. Pemerintah pusat melalui LKPP, Kemendagri, dan Kementerian Desa dapat mengirimkan mentor teknis secara virtual setiap triwulan untuk memberikan asistensi regulasi, validasi dokumen, hingga pelatihan penggunaan aplikasi pengadaan. Pendampingan ini bisa dilengkapi dengan program benchmarking dan studi tiru ke daerah-daerah yang lebih maju dalam tata kelola PBJ, agar para pelaku pengadaan di 3T mendapatkan inspirasi dan pengalaman nyata tentang praktik terbaik yang relevan dan aplikatif.
Dengan enam strategi besar tersebut-yakni reformasi regulasi, penguatan fiskal, koordinasi multisektor, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, dan pendampingan berkelanjutan-maka proses PBJ di daerah 3T memiliki peluang besar untuk keluar dari stagnasi dan bisa bertransformasi menjadi sistem yang lebih tanggap, inklusif, dan berorientasi hasil.
8. Penutup
Pengadaan barang dan jasa di daerah 3T bukan sekadar soal logistik atau anggaran, melainkan menjadi barometer nyata dari komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Ketika pengadaan di wilayah perkotaan dapat berjalan dengan dukungan sistem yang mapan, SDM yang memadai, dan akses teknologi yang luas, maka kondisi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal justru memperlihatkan betapa lemah dan timpangnya infrastruktur institusional yang ada. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam pelayanan publik, tetapi juga menghambat laju integrasi nasional yang berkeadilan.
Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan proses PBJ di wilayah 3T memang sangat kompleks dan multidimensi. Mulai dari kendala fisik seperti cuaca ekstrem, jarak tempuh antarwilayah yang jauh, hingga keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di level operasional. Tak kalah serius adalah keterbatasan literasi digital, lemahnya akses internet, minimnya jaringan distribusi barang, serta belum memadainya desain kebijakan fiskal yang secara spesifik berpihak pada kebutuhan wilayah 3T. Dalam konteks seperti inilah, pendekatan kebijakan yang bersifat sentralistis dan normatif tidak lagi memadai, melainkan harus digantikan oleh pendekatan kebijakan yang kontekstual, progresif, dan inovatif.
Dengan menerapkan strategi mitigasi seperti reformasi regulasi berbasis kekhususan daerah, alokasi anggaran afirmatif, penguatan koordinasi antarinstansi, mekanisme swakelola berbasis pemberdayaan masyarakat, percepatan digitalisasi, dan sistem mentoring berkelanjutan, maka proses PBJ di wilayah 3T akan mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi kecepatan, efisiensi, maupun akuntabilitas. Hal ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi, serta penciptaan peluang kerja lokal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Pada akhirnya, keberhasilan reformasi pengadaan di daerah 3T bukan hanya soal memperbaiki prosedur, tetapi soal mengubah paradigma. Dari paradigma birokrasi yang statis dan seragam, menuju paradigma pelayanan yang tanggap terhadap keragaman kondisi wilayah. Ketika PBJ di wilayah paling tertinggal bisa berjalan cepat, transparan, dan berdaya guna, maka itulah saat di mana negara benar-benar hadir bagi seluruh rakyatnya-tanpa terkecuali.